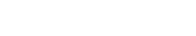Chapter 172 - The Moments
Chapter 172 - The Moments
"Jadi, apa cita-citamu, Dai?" Tanyanya saat itu padaku.
Jujur, saat itu aku sendiri mana tahu aku ingin menjadi apa dan memiliki cita-cita apa.
Mau menjadi Presiden? Ah, terlalu kekanakan sekali. Jadi guru? Aku sedikit tidak bisa mengontrol emosiku pada anak kecil, tapi ketika aku melahirkan Jason, ternyata mengajar anak kecil itu menyenangkan.
Kugelengkan kepalaku saat itu. "Aku belum tahu, Rez. Kalau kamu?" tanyaku balik.
"Kok belum tahu? Padahal sebentar lagi masa depan di depan kita, loh."
Reza sama sekali belum menjawab pertanyaanku mengenai cita-citanya. Jadi aku mengikuti sana arusnya.
"Aku memang belum tahu. Lagi pula, cita-cita apa yang cocok untukku?" Tanyaku padanya meminta saran.
Dengan lucunya dan ketampanannya, Reza seolah berpikir akan sesuatu. Menatap penampilanku saat itu yang benar-benar sangat desa.
"Wanita karir. Kamu cocok jadi itu," imbuhnya.
Dan di sinilah aku. Secara tidak langsung, ucapannya menjadi doa yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Aku menjadi wanita karir berkat Reza. Entah ia melantunkan namaku dalam doanya atau sekadar asal bicara saat itu.
Aku juga ingat, saat itu aku tertawa keras. Menertawai jawaban Reza tentang aku yang cocok jadi wanita karir. Apa dia bercanda? Pikirku saat itu.
"Aku jadi wanita karir? Yang benar aja, Rez?! Memangnya terlihat sangat cocok untukku?" tanyaku tidak memercayainya.
Reza mengacak-acak rambutku dan berdecak. "Cocok nggak cocok, tapi aku rasa kamu akan jadi wanita karir dengan nama yang besar."
"Aminkan aja, deh. Lalu apa cita-citamu? Kamu belum sempat menjawab pertanyaanku, loh," tanyaku akhirnya.
Tanpa merasa ragu akan jawabannya, Reza bahkan saat itu langsung menjawab. "Aku mau jadi pilot."
Aku menganga. Iya, aku terkejut dengan jawabannya itu. Bagiku, menjadi seseorang pilot atau berprofesi seperti itu sangat susah. Bahkan aku sempat meremehkan Reza saat itu.
"Iya, aku mau jadi pilot, Dai. Jangan kaget, dong," katanya mengulang hal yang sama.
"Ya, gimana nggak kaget. Itu kan, susah, Rez."
"Memangnya kalau susah nggak layak untuk dicoba?"
Dari situ aku tahu betapa positif dan niatnya seorang Reza, mantan kekasihku.
Apakah ada penyesalan dalam diriku karena berpisah dengannya? Tidak. Sama sekali tidak. Mungkin saat awal-awal aku sempat sedih. Yah, kalian tahu sendiri bagaimana aku terpisahkan darinya oleh ulah Zen saat itu.
"Daisy, aku janji akan bahagiain kamu dengan caraku," ucapnya tiba-tiba seraya merengkuh kedua tanganku.
Rengkuhan tangannya persis sekali dengan apa yang dia lakukan sekarang. Dia dengan seragam pilotnya dan aku sebagai wanita karir yang ia ucapkan kala itu.
"Daisy?" suaranya menyeruak ke telingaku. Membangunkanku dari lamunan akan momen-momen di mana aku baru saja kembali ke sana.
Aku tersentak dan mengedipkan kedua mataku menatapnya. Lalu aku sadar bahwa aku sedang ada di dunia masa depan.
"Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya menatapku.
"Errr ... Itu," aku menggaruk hidungku yang tak gatal. "Aku ingat saat-saat di mana kita membicarakan tentang cita-cita, Rez," tambahku.
Reza tersenyum mendengar jawabanku. Aku rasa dia senang sekarang. Apalagi membicarakan masa lalu.
"Aku pikir kamu nggak ingat akan itu," ucapnya jujur.
"Tentu saja aku ingat semuanya," kataku menghela nafas.
Kutatap Reza pandangan yang syahdu dan mengatakan, "terima kasih, ya. Kamu menjadikanku wanita karir sekarang. Aku masih nggak sangka."
***
Aku menceritakan semua hal pada Jeremy tentang Reza. Bersyukur Jeremy bukanlah tipe seorang yang cemburu. Ia bahkan tidak mempermasalahkan bagian di mana aku memeluk Reza untuk terakhirnya.
Berjalan bersama Jeremy memang membawa hal-hal positif yang aku sama sekali tidak menyangkanya.
Jeremy selalu mengatakan bahwa kejujuran membawa kebaikan. Sepahit apa pun kejujuran itu, walau kita yang menyampaikannya, maka akan terdengar lebih lega dari pada dapat dari orang lain.
"Jadi, dia sudah terbang?" tanya Jeremy.
"Sepertinya iya," jawabku seraya menatap arlojiku.
Sebenarnya aku tidak tahu pukul berapa Reza terbang. Tapi mengingat pertemuan kami yang sudah lebih dari beberapa jam setelahnya, kurasa ia sudah terbang.
"Apa kamu sedih, Dai?" tanya Jeremy.
"Kenapa aku harus sedih?"
"Yah, dia kan orang yang secara nggak langsung membuat kamu jadi seperti sekarang," jawab Jeremy.
Aku mengaduk-aduk makananku seraya memikirkan jawaban Jeremy.
Aku tidak tahu apakah aku sedih atau hanya sekadar merasa bingung harus bereaksi apa.
"Sepertinya sedih bukan hal yang pas, ya. Dia kan, pergi untuk bekerja. Lagi pula aku hanya merasa bersyukur karena pernah mengenalnya dan menjadikanku seperti sekarang ini."
Jeremy tersenyum mendengar jawabanku. Ia lalu menyentuh daguku dan menggeleng-gelengkan kepalanya.
"Aku senang dipertemukan kamu, Daisy," ucapnya tiba-tiba.
Merasa malu dan tersipu, aku menunduk. Jeremy selalu bisa membuat pipiku memerah.
"Berhenti bicara yang manis-manis padaku, Jer. Aku malu," tangkasku.
Ia tertawa. Demi apa pun Jeremy tertawa ketika aku jarang sekali mendengar sekaligus melihatnya tertawa.
"Oh ya, apa kamu masih nggak apa-apa dengan Ricky?" tanyaku padanya.
"Kenapa tiba-tiba bicara soal dia, Daisy?"
"Karena aku tahu Ricky bukan tipikal yang berhenti begitu saja, Jer."
"Dia akan kuurus. Kamu nggak perlu khawatir."
Aku menautkan kedua alisku. Sejak kapan Jeremy mengurus sesuatu yang berbau seperti itu? Rasanya mendengarnya saja membuat bulu romaku berdiri.
"Urus? Kamu apakan dia?" tanyaku penasaran.
"Belum aku apa-apakan. Hanya saja aku akan mengurusnya kalau dia masih berkeliaran mengganggumu."
Sepertinya Jeremy memang berubah total. Aku memang tidak tahu banyak apa saja yang ia lewati. Bagaimana ia mengatasi masalah seperti itu dan tentang perubahannya yang sangat ekstrem.
"Jer ... Jangan pakai kekerasan, OK? Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa," ucapku melembut.
"Aku nggak pernah pakai kekerasan, Dai. Aku cuma ingin membuatnya sedikit jera."
"OK, lupakan tentang itu. Bagaimana kalau kamu cerita tentang apa rencana kita ke depan?"
Entah malaikat yang masuk dari mana, tiba-tiba membuatku membicarakan hal yang serius itu.
Dasar bodoh! Kalau aku bicara begitu, sudah pasti niatku ingin serius padanya dan Jeremy sekarang terkejut melihatku. Sial!
Jeremy membuka mulutnya lalu menutupnya kembali. Sesuatu yang ingin ia bicarakan, ia telan kembali. Aku penasaran akan apa jawabannya.
"Apa kamu benar-benar mau serius, Dai?" tanyanya.
Tidak! Aku belum siap, batinku. Jangan sekarang. Tadi itu hanya ucapan bodoh yang asal keluar begitu saja.
"Maaf, lupakan pertanyaan tadi, Jer. Aku ... Aku hanya bingung mau membicarakan apa," kataku akhirnya.
Jeremy tersenyum hangat. Aku tahu hatinya pasti terluka lagi. Ia bahkan pandai menutupinya. Padahal seharusnya jangan begitu.
"Aku tahu. Ya udah, bagaimana kalau kita membicarakan ulang tahun Jason?" usulnya.
***
Selama ini aku tidak pernah merayakan ulang tahun anakku. Satu karena aku tidak suka pesta. Dua karena aku tidak suka basa-basi dengan orang asing. Tiga karena aku tidak ingin saja.
Sekarang, Jeremy sibuk menyiapkan segalanya untuk Jason. Jason belum tahu kalau ulang tahunnya akan dirayakan oleh kami. Ia hanya tetap bermain dan bermain dengan tawanya khas anak kecil.
Selama Jason ulang tahun, aku hanya bisa membelikannya kue dan kemudian meniupnya secara berduaan.
Raka, Reina, Ibu dan Papa juga tak lupa selalu memberikan kado Jason di setiap ulang tahunnya.
Ulang tahun Jason dirayakan di restoran Fast Food yang mana selalu bisa mengadakan pesta ulang tahun di sana.
Sekarang aku bingung pada siapa aku harus mengundang teman-teman Jason. Di sekolah Jason memang terkenal ramah, persis sekali seperti Raja.
"Jadi, kamu mau undang siapa?" tanya Jeremy akhirnya.
"Hmm ... Nanti biar aku kasih undangan ke gurunya Jason aja."
"Ayolah, jangan lesu. Ini kan, ulang tahun anakmu, Daisy."
"Tapi ini terlalu berlebihan, Jer. Aku ... Aku nggak pernah membuat pesta untuknya."
"Dan sekarang kamu akan membuatnya. OK? Jangan khawatir, ya."
Aku gugup. Padahal ini pesta ulang tahun anakku. Mungkin juga karena aku tidak pernah mengadakan pesta, jadi kesannya selalu aku yang gugup pertama kali.
"Apa keluargamu akan datang?" tanyaku berhati-hati.
"Apa kamu mau aku mengundang mereka?" tanyanya balik.
Entah kenapa jika Jeremy begitu, seolah semua beban dilimpahkan padaku. Padahal aku tahu niatnya adalah menawarkan jika aku siap dan tidak siap.
"Apa mereka nggak apa-apa bertemu denganku?" tanyaku ketakutan.
"Bahkan mereka menanyaimu selalu setiap kits menghabiskan waktu bersama, Dai."
Aku terkejut. Selama ini Jeremy tidak pernah mengatakan bahwa keluarganya menanyaiku. Baru sekali ini aku tanya, ternyata mereka semua masih peduli padaku seberapa besar aku membuat Jeremy terluka.
"Itu terserah kamu aja, Jer," ucapku kemudian.
Jeremy mengacak-acak rambutku dan tersenyum. "Kalau begitu, ayo, aku antar kamu ke salon," ajaknya.
Sampai salon, Jeremy membiarkanku melakukan perawatan sementara dirinya menunggu di ruang tamu.
Kalau begini, aku jadi ingat masa-masa saat bersama Zen. Aduh, kenapa hari ini aku diingatkan oleh banyak hal? Bahkan aku sendiri menikmati momen yang aku ingat itu.
Zen ... Dia pernah berada di posisi Jeremy. Tentu saja dengan anak buah yang banyak untuk menjagaku. Berlebihan tapi harus aku akui, begitulah caranya menjagaku.
"Suaminya, ya?" tanya si terapis. Aku melihat jelas nama yang tertera di bajunya. Namanya Alda ternyata.
"Oh, bukan. Dia ... Teman," jawabku ragu.
"Ih, Mbak. Kalian kelihatan seperti sepasang suami istri. Bagaimana mungkin cuma teman?" Tanyanya.
Duh. Aku harus menghela nafas. Sepertinya dia hanya ingin mengajak bicara agar kelihatan suasana tidak canggung.
"Masa, sih?" tanyaku meneruskan ucapannya.
"Iya. Masnya cocok tahu jadi suami Mbak. Dia rela nungguin tu," ucap si Alda mengarah melihat cermin.
Jeremy sedang membaca-baca majalah dan sesekali ia menatap ponselnya. Aku juga heran kenapa aku tidak jadi istrinya saja saat itu? Malah menggagalkan semuanya.
"Dia ... Sebenarnya mantan saya, Mbak. Dan yah, kami sepertinya sedang melakukan pendekatan lagi," ucapku.
"Ih Mbak, mantan kok melakukan pendekatan lagi? Ini pasti salah satunya ada yang ragu. Kalau Mas-nya sih nggak kelihatan ragu. Hmm ... Jangan-jangan, Mbaknya yang ragu, ya?"
Pernyataan si Alda benar-benar membuatku terkejut. Ia terapis, tapi bisa sekali menilai langsung begitu. Apalagi penilaiannya itu benar-benar terjadi.
"Hmm, ya ... Kira-kira begitu," ucapku dengan senyuman.