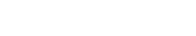Chapter 125 - Only You Deserve Him
Chapter 125 - Only You Deserve Him
Raka mengerutkan dahinya karena memang aku masuk ke dalam ruangannya hanya untuk mengatakan itu. Padahal bisa saja memberitahunya melalui dial telepon kantor. Tapi aku lebih senang berbicara langsung. Yah, sekaligus mencoba untuk memberanikan diri.
"Tunggu, kamu mau ketemuan dengan Zen? Apa aku nggak salah dengar?" tanyanya bingung.
"Ya, kamu nggak salah dengar, Raka. Ada hal yang ingin kubicarakan padanya."
Kududukkan bokongku di kursi depan mejanya dan bersandar di sana.
"Kamu yakin?"
Aku tahu masa laluku bersama Zen dinilai cukup rumit dan sangat tidak baik. Tapi seharusnya mereka berpikir bahwa manusia bisa saja telah berubah. Entah kenapa keluargaku masih tidak begitu percaya terhadap perubahan Zen.
"Kamu nggak sedang merencanakan balikan padanya, kan?" tanya Raka serius.
Oh? Aku membelalakkan mataku sebagai reaksi yang tidak kupikirkan di otakku. Sekalipun Rosi memintaku, tapi aku tidak bisa kembali pada Zen. Maksudku, aku tidak tahu ke depannya seperti apa.
"Udahlah, Raka. Aku cuma ingin memberitahu kamu agar nggak terus mencariku nantinya. Aku permisi," kataku lantas berdiri dan keluar ruangannya tanpa menunggu balasan darinya.
Saat jam kantor selesai, sebelumnya aku sudah menerima pesan dari Zen bahwa ia sudah sampai di tempat.
Zen memang selalu tepat waktu. Walau aku yang mengajaknya bertemu, dia selalu datang lebih awal. Kepribadiannya yang santun ini kadang membuatku sedikit luluh.
Aku keluar menuruni anak tangga depan kantor dengan perlahan. Walau hanya beberapa anak tangga, tapi begitu saja nafasku sudah memburu.
Saat aku masuk ke mobilnya, aku berusaha mengatur nafasku. Lalu tangan Zen mengulurkan sebotol air mineral untukku. Kuterima dan kuteguk air itu karena memang aku membutuhkannya.
"Istirahatlah selagi berjalan. Biar aku yang menentukan tempatnya," katanya.
Selalu begitu. Ia selalu memberikan aturan dan perintah tanpa menunggu lawannya menolak atau berbicara.
Zen masih kesulitan untuk menghadap publik. Sehingga ketika ia memesan sebuah tempat, cukup privat dengan minim tamu. Bahkan sepertinya hanya beberapa tamu penting saja dengan penjagaan rahasia yang ketat.
"Aku harap kamu nggak keberatan," katanya seraya turun dari mobil.
Tentu saja aku keberatan atau tidak, tetap saja aku tidak bisa menolak. Well, lebih tepatnya Zen tidak bisa menerima penolakan.
Zen menuntunku ke dalam resto dan memilih tempat yang terkesan sangat pojok. Setiap tempat memiliki pembatas dan pintu mini yang mana hanya memperlihatkan atas kepala dengan kaki.
Aku memilih menu sesuai dengan apa yang kumau. Walau khas masakannya sedikit begitu menu barat, tapi beruntunglah ada yang namanya nasi.
"Apa kamu mau mulai bicara sekarang, Daisy?" tanyanya setelah kami memesan pesanan kami pada pelayan.
"Apa nggak sebaiknya menunggu setelah makan?"
"Sekarang aja."
Aku berdeham mengatur suaraku. Perintahnya sudah pasti tidak bisa ditolak. Jadi kukatakan saja.
"Tadi, Rosi menemuiku," ujarku padanya.
Tidak ada ketegangan dalam ekspresinya. Hanya tenang dan datar. Ia menungguku untuk melanjutkan ucapanku.
"Intinya, dia memintaku untuk dekat denganmu karena kamu bisa menjamin kehidupanku, terutama anakku," jelasku singkat.
Kini wajahnya memperlihatkan ketegangan. Ia mungkin berpikir bahwa Rosi datang hanya sekadar untuk mencurahkan isi hatinya. Nyatanya, di luar dugaannya.
Posisi Zen terlihat gusar. Ia lalu melepas jasnya dan mengendurkan dasinya kemudian kedua lengan panjangnya ia gulung ke atas.
"Dia bilang seperti itu?" tanyanya seolah baru sadar akan apa yang kukatakan.
Aku bergumam. Menunggu reaksi dan balasan apa yang akan ia katakan.
"Jangan pikirkan itu. Dia sedang kalut. Maklumi aja," katanya kemudian.
"Lalu, kamu mencampakkannya begitu saja?"
"Aku nggak mengatakan begitu, Daisy. Bahkan aku belum mengatakan rencanaku," katanya membela diri.
Oke, memang Zen belum mengatakan apa pun tentang apa yang akan ia lakukan pada Rosi. Tapi, matanya memang menunjukkan ketidakinginannya bersama Rosi dalam beberapa waktu atau mungkin selamanya.
"Kalau begitu katakan. Jangan bilang kamu mencampakkannya setelah kamu menghamilinya, kemudian keguguran."
Zen menghembuskan nafasnya. "Aku... nggak akan mencampakkannya. Tapi pilihan ada padanya. Dia yang tahu persis seperti apa perasaanku padanya. Soal kehidupannya, aku menjamin semuanya."
Oh... Jadi sekarang ia menggunakan perasaannya sebagai tameng demi bisa meninggalkan Rosi secara tidak langsung.
"Sejak kapan kamu begitu emosional, Zen?" tanyaku mengalihkan.
"Sejak... perceraian itu."
"Tapi kamu selalu bermain dengan wanita lain selain Rosi, bukan?" tanyaku lagi.
"Aku frustrasi, Daisy. Itulah cara yang kugunakan untuk melupakan yang bisa kulupakan."
Zen sama sekali tidak terdengar terkejut ketika aku bertanya bagian itu. Sepertinya ia sudah tahu bahwa aku tahu semuanya.
Tak lama pelayan datang dengan membawa hidangan kami. Menghentikan pembicaraan kami mau tak mau.
"Makanlah. Kamu bisa bertanya apa pun setelah ini. Atau membahas apa pun," katanya memerintah.
Aku makan dengan perlahan. Menikmati setiap kunyahan yang kutelan hingga rasa lapar itu berkurang dan kemudian merasa kenyang.
Sementara itu, Zen masih memotong dagingnya perlahan-lahan dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan profesional.
Sekejap aku takjub. Sejak dulu sebenarnya. Bagaimana bisa hanya memasukkan potongan daging steik saja ia bisa terlihat begitu pro dan sempurna? Mencengangkan.
Namun ada yang berbeda darinya. Ia tidak terlalu mengejarku seperti dulu. Seakan membiarkanku memilih dan menjalaninya seperti air yang mengalir. Seharusnya aku senang, bukan? Artinya aku tidak perlu repot merasa risi atau semacamnya.
Tiba-tiba aku menangkap kilatan matanya yang tajam ke arah cincinku. Pasti dia berpikir sesuatu.
"Itu... Cincin siapa?" tanyanya.
"Milik Jeremy. Dia pernah melamarku dan aku memintanya untuk kupakai."
Alisnya terangkat satu mencoba mencerna setiap ucapan yang kulontarkan.
"Jadi kamu sekarang berhubungan dengannya?"
"Zen... Aku rasa obrolan kita selesai di sini. Sepertinya nggak ada yang perlu dibicarakan lagi," kataku mengakhiri obrolan ini.
Dari pada ia bertanya padaku dan aku tidak memiliki jawaban, sebaiknya aku segera menghindar. Jadi aku berdiri dsn meraih tasku.
Mendadak tubuhku sedikit limbung, lalu Zen dengan tangkas menahanku.
"Hei, kamu nggak apa-apa?" tanyanya mulai panik.
Tadi itu pusing atau darah rendah? Semua penglihatanku terasa buram dan gelap. Tapi untung saja hanya sekejap.
"Ya... Nggak apa-apa. Thank's."
"Ayo, aku antar pulang," katanya perlahan masih memegang diriku.
Zen membuka pintu samping kemudi untukku dan ia segera menyusul. Gerakannya benar-benar cepat dan ia terlihat khawatir. Padahal aku sudah tidak kenapa-kenapa.
Rahangnya mengeras dan pandangannya begitu tajam ketika ia mulai mengemudikan mobilnya. Bahkan lajunya sangat pelan dan aku mulai kesal.
"Aku nggak apa-apa, Zen. Jangan berlebihan," kataku memulai percakapan.
Dia hanya diam. Aku tahu saat ini dirinya tengah berguncang hebat lantaran ia habis kehilangan anaknya yang dikandung Rosi. Sehingga apa pun yang kurasakan seperti tadi, membuatnya kembali teringat pada kejadian itu.
"Maaf, aku membuatmu khawatir," kataku sekali lagi seraya memandangnya.
Ekspresi Zen melembut dan aku bisa melihat cengkeraman dua tangannya mengendur sehingga tidak begitu kelihatan urat-uratnya yang tercetak jelas.
"Maafkan aku, Daisy. Aku memang khawatir dengan tingkat yang berlebihan," katanya membalas.
Entah kenapa aku merasa lega jika ia sudah membalas ucapanku dengan ekspresinya yang melembut. Jadi, aku hanya kembali diam dan menatap luar jendela mobil.
Sampai rumah, aku langsung keluar dan membiarkan Zen pergi. Aku memang tidak menawarinya untuk berkunjung atau bertamu.
Aku bisa bernafas lega karena akhirnya tidak terjadi sesuatu yang mengenakkan terhadap satu sama lain. Tadinya pikiranku berkelit karena bisa saja Zen memanfaatkan keadaan dan kami seks bersama.
Zen juga cukup berhasil membuatku lupa sejenak dengan Raja. Maksudku, aku seperti sedang berhadapan dengan Raja dalam bentuk versi Zen.
"Tadi itu Zen?" tanya Ama yang muncul dari dalam kamarnya.
Oh. Aku hampir lupa bahwa Ama masih di sini.
"Hmm, ya. Oh ya, bagaimana? Apakah kamu jadi tinggal di sini, Ama?" tanyaku.
"Ya... Sepertinya begitu. Orang tuaku mengenal kamu, jadi sepertinya nggak masalah buat mereka. Dan omong-omong, ada apa dengan Zen?"
Tambah satu orang yang penasaran membuatku lelah untuk menceritakan dari awal. Aku pun hanya memberitahukan intinya saja pada Zen.
"Ya, ampun Daisy! Padahal kalau dipikir pun, nggak usah menemuinya nggak apa-apa, tahu," responsnya sedikit kesal.
Yah, aku juga pikir begitu. Entah kenapa aku menjadikan alasan itu sebagai pertemuan kami. Padahal sebenarnya tidak perlu dan cukup mengabaikannya saja.
Kupandang Ama dengan pandangan 'aku tahu dan kamu paham aku seperti apa' padanya. Lalu Ama pun menghela nafasnya dan ikut duduk bergabung denganku.
Kami mulai kembali mengobrol sesuatu yang dirasa tidak perlu, ala-ala khas wanita.
***
Hari libur cukup membantuku bisa santai. Sejak kehamilan ini rasanya aku malas untuk melakukan sesuatu. Jadi, kubiarkan Ama melakukan apa yang ia mau. Bukan bermaksud menjadikannya pembantu, tapi memang Ama ahli dalam rumah tangga biar pun ia sekarang hanya berstatus lajang.
Sayangnya dokter Margaret menyuruhku untuk melakukan olahraga. Olahraga sederhana kumulai dari yoga saja. Mengikuti tutorial Youtube dan melakukannya di taman belakang dengan pemberitahuan pada Ama bahwa aku tidak mau diganggu.
Bukannya aku melakukan yoga sesuai instruksi, malahan dia kembali muncul setelah lama tidak muncul.
Raja.
Mataku tetap terpejam dan aku tidak bisa membukanya. Ia seakan ingin mengatakan sesuatu padaku setelah beberapa saat menatapku.
"Aku harap kamu mau berjanji untuk bersama Jeremy, Daisy," katanya.
Suaranya menggema. Seperti aku dan dirinya berada di satu lorong sempit dan suaranya menggema mengisi lorong itu.
Konsentrasiku terpecah karena kehadirannya. Entah kenapa Raja ingin aku menepati janjinya. Padahal ini bukan lagi mimpi.
"Aku tahu dia baik untukmu dari pada... Zen." Keningnya berkerut ketika ia menyebutkan nama Zen. Sayangnya bibirku tidak bisa terbuka dan bertanya kenapa.
Padahal untuk menuju hubungan yang serius saja aku belum memikirkannya. Kehilangan Raja membuatku berpikir dua kali lipat untuk memulai hubungan baru. Lagi pula, kenapa juga Raja memaksaku seperti ini? Apakah dia adalah benar-benar dia atau hanya sekadar halusinasiku?
"Percayalah padaku, Sayang... Aku melihat semua yang mereka lakukan. Dan sejauh ini, cuma Jeremy yang pantas untukmu."