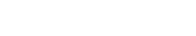Luka
Luka
"Lukanya tidak ada yang parah, paling besok juga sudah hilang," jawab Lyra, mengamati Rava yang tengah membalut luka di lengan kirinya. Sang bidadari tetap memajang ekspresinya yang biasa, samasekali tak meringis kesakitan.
Untuk kesekian kalinya, Rava mengecek tutorial mengobati luka di ponselnya. Tangannya benar-benar kikuk merangkai perban di tangan Lyra. Luka-luka di punggung, kaki, dan wajah Lyra sudah diperban, hanya tinggal satu yang kini digarap Rava. Rava sendiri yang menawari untuk membantu karena kasihan melihat Lyra kerepotan membalut luka di tangan. Lyra sampai harus menggunakan mulut untuk membuat simpul perban.
"U-udah." Sambil meringis, Rava mengamati bebatan perban hasil karyanya yang agak amburadul, walaupun cukup kencang dan simpulnya bagus. Bebatan itu terlihat janggal dibandingkan dengan bebatan-bebatan lain di tubuh Lyra yang jauh lebih rapi. "M-maaf kalau salah."
Lyra kembali mengamati hasil karya Rava itu sejenak, kemudian berkata, "Terimakasih. Ini cukup, kok"
"Sama-sama." Rava beranjak untuk merapikan kotak p3k. Namun, baru beberapa detik, ia menghentikkan kegiatannya. Ia teringat sesuatu di pertarungan melawan Zita tadi sore. "Waktu di sana, aku ngeliat jenazah bidadari berbaju merah marun itu di ...."
"Ah, kamu sudah melihatnya, ya?" potong Lyra datar. "Dia tidak dimakan. Mulut Piv memang digunakan untuk portal dari dan ke dunia kami. Kedatanganku juga dari sana."
"Begitu, ya. Aneh banget." Rava melanjutkan kegiatannya merapikan kotak p3k. Merasa dirinya harus membiasakan diri mendengar atau melihat sesuatu yang absurd, Rava berusaha untuk bereaksi senornmal mungkin. "Bagaimana rasanya melewati ...."
"Jangan menengok ke belakang dulu," cegah Lyra cepat. "Aku sedang buka baju ...."
Rava yang sudah akan memutar tubuhnya langsung mematung. "K-kenapa?"
"Maaf, aku tidak berkenan menceritakan tentang kedatanganku ke sini. Yang jelas, perpindahan antar dimensi lewat mulut Piv itu samasekali tidak menyenangkan."
"Bukan itu ...." Rava kesulitan merangkai kata. "Kenapa kamu buka baju di kamarku? Kalau mau ganti baju, kenapa nggak di kamar ibu aja?"
"Sudah kubilang, kan. Untuk bisa lebih cepat pulih, bidadari harus dekat dengan tuannya. Itu supaya transfer energi kehidupan ke tubuh bidadari jadi lebih lancar. Semakin banyak bagian kulit bidadari yang terekspos, semakin lancar pula transfer energi kehidupan itu," terang Lyra, kemudian berkata. "Sudah."
"S-sudah bagaimana?" Wajah Rava mulai memerah. "Kamu sedang nggak pakai baju, apanya yang sudah?"
"Aman, kok."
Bergerak kaku bak robot, Rava menoleh kepada bidadarinya itu, hanya untuk kembali membelakanginya. Itu sama sekali tidak aman. Lyra tengah tengkurap dengan punggung mulus yang terbuka. Dada besarnya yang juga tak terlindungi apa pun kini menekan permukaan tikar.
"Aman matamu sengklek!" gerutu Rava, memegangi keningnya.
"Paling tidak, aku memakai celana dalam."
Rava menghela napas, lantas duduk di kursi komputernya. Sepertinya, dia harus benar-benar membiasakan diri dengan situasi-situasi yang bikin wajahnya memerah seperti ini. "Benar-benar harus buka baju seperti itu, ya?"
"Punggung bidadari adalah bagian yang rasio penyerapan energinya paling tinggi," terang Lyra lirih. "Sebelum datang ke sini, kami punya sayap. Bisa dikatakan, sayap itulah sumber kekuatan kami."
"Ke mana sayap kalian kalau begitu?" Mengalihkan pikirannya dari tubuh Lyra, Rava membuka ponselnya.
"Mereka mencabutnya sebelum kami tiba di sini. Sang pemenang akan mendapatkan sayapnya lagi dan berhak menjadi ratu."
"Pemerintahan duniamu itu memang kejam, ya? Aku membayangkan sayap itu adalah bagian dari tubuh kalian. Kalian pasti menggunakannya setiap hari, seperti tangan dan kaki. Aku nggak bisa membayangkan diriku kehilangan tangan atau kaki."
Lyra sedikit menghela napas. "Kalau sayap kami masih ada, orang-orang dari dunia yang tempatnya dijadikan arena pemilihan pasti akan keheranan. Pihak penyelenggara tentunya tak mau mendapat perhatian yang tidak perlu .... Tapi, aku yakin alasan sayap kami diambil bukan itu saja. Pasti ada tujuan lain."
"Ya, ya, ya ...," timpal Rava datar, benar-benar memutuskan untuk tidak bereaksi terlalu berlebihan. Kalau sedikit-sedikit kaget karena cerita absurd atau kelakuan Lyra, kasihan jantungnya.
"Rava, kamu sedang mengerjakan sesuatu di komputer, ya?"
"Hm?" Rava merasa dadanya sedikit bergejolak mendengar hal itu, tetapi sekali lagi dia berusaha bersikap biasa. "Nggak, cuma baca berita di hape."
Ya, tanpa kemampuan melukisnya, apa yang mau dikerjakan di komputer?
"Berarti kamu bisa melakukannya di kasur, kan? Mendekatlah kepadaku," pinta Lyra pelan.
Melakukan? Melakukan apa? Melakukan itu? Seumur hidupnya, ini adalah panas tertinggi yang Rava rasakan di wajahnya. Ia pun bangkit sambil menggebrak meja, berbalik dan berseru, "Ini udah kelewatan, Lyra!"
Dan Rava langsung berbalik kembali saat melihat tubuh mulus Lyra yang hanya terlindungi celana dalam warna biru muda itu.
"Huh?" Lyra sedikit mengernyit. "Kamu kenapa, sih? Maksudku, kamu bisa membaca berita di kasur, kan? Aku jadi bisa dekat dengamu. Kan sudah kubilang, Pemulihan seorang bidadari akan semakin lancar kalau dia semakin dekat dengan tuannya."
"Ah." Jawaban datar keluar dari mulut Rava. "Oke."
Merasa seperti orang bodoh, Rava bergerak ke kasurnya sambil menutupi pandangannya dengan tangan.
"Sebenarnya ada cara yang lebih efektif lagi," ujar Lyra ketika Rava sudah duduk di kasur dengan membelakanginya. "Kamu jelas tidak mau, aku pun tidak mau ...."
"Stop, jangan dibahas lagi," sela Rava dengan wajah yang masih merah. Meski dugaannya tentang 'cara yang lebih efektif' itu belum tentu benar, Rava tak mau mendengar lanjutan dari penjelasan bidadarinya itu. Jantungnya tidak kuat. "Kamu nggak pindah ke kasur aja? Nggak dingin di situ?"
"Aku lebih senang di sini. Lebih sejuk," jawab Lyra.
"Kalau emang mau di kasur, bilang aja." Rava membenarkan posisi duduknya yang mulai tidak nyaman. Tanpa sengaja, dia melihat bebatan perban di paha Lyra. Dengan tubuh seramping itu, Lyra bertempur dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau hanya mendengar saja dan tidak melihatnya secara langsung, Rava pasti tak akan percaya. "Kamu nggak mempertimbangkan untuk berhenti bertarung saja? Kamu kan ...."
Rava tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia merasa tak berhak. Dia telah menutup jalan Lyra mencapai tujuannya.
"Masih ada monster yang harus dibasmi. Lagipula, cepat atau lambat bidadari yang lain akan datang untuk membunuhku demi. Aku harus terus bertarung untuk membuka kemampuan baru," timpal Lyra pelan.
"Begitu, ya."
Selanjutnya, keheningan menyelimuti mereka berdua. Mendengar dengkur halus bidadarinya, Rava memutuskan untuk ikut berbaring. Membelakangi Lyra, pemuda itu menatap tembok. Kalau saja masih bisa, dia akan melukis untuk sekedar mengalihkan pikirannya dari kengerian yang tadi dilihatnya.
Bidadari yang mati mengenaskan. Bidadari gila yang haus darah. Bidadari yang mereka tinggalkan untuk menyelamatkan diri.
Ada manusia yang kehilangan nyawa juga. Rava bertanya-tanya, kalau bidadarinya tewas, apakah dia juga akan dibantai?
Sedari tadi, ritme degup jantung Rava tak kunjung menurun.