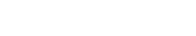41. Dilema
41. Dilema
Rava fokus menatap layar televisi yang menampilkan grafis dua lelaki yang bertarung. Tak kalah dengan Stefan, ia terus menekan-nekan tombol di stiknya dengan cepat dan akurat. Begitu karakternya mengalahkan jagoan Stefan, Rava baru menjawab, "Aku juga mikir gitu. Kayaknya, siapa pun yang ngirim mereka itu nggak bisa mendeteksi lokasi para bidadari. Kalau bisa, mereka udah ngirim monster ke tempat bidadari tinggal di bumi."
Stefan menyandarkan punggungnya ke sofa, mendesah pelan. "10-0. Aku kalah lagi."
"Kalau di dunia kami, mereka muncul sembarangan untuk membuat teror. Katanya sih, agar rakyat takut, sehingga kalau pihak yang mengirim para monster berhasil mengambi-alih pemerintahan, maka rakyat jadi tunduk kepada mereka," sambung Ione yang duduk di karpet, seperti biasa memandangi foto-foto pria kekar di ponselnya. "Yah, orang seperti pembantai dari tenggara juga muncul sembarangan, sih. Dan terkadang dia lebih kejam dari monster."
"Apa benar perkataan Lois kemarin? Zita itu pembantai dari tenggara?" tanya Kacia yang duduk sofa lain, terdengar cemas. Ia menghentikan kegiatannya membaca komik di ponsel pemberian Stefan.
"Kalau benar, ini mimpi buruk," timpal Lyra, duduk di karpet sambil menyentuh-nyentuh layar ponsel dengan jari telunjuk. Gerakannya begitu kaku seperti orangtua yang baru diperkenalkan dengan teknologi. "Aku yakin, sebenarny dia sedang menahan diri. Mau sekejam apa pun Zita, dia tak bisa melanggar ketentuan pihak penyelenggara. Aku yakin, kemampuan merusaknya jauh lebih gila dari apa yang kita lihat."
Rava langsung memegangi tengkuknya, yang seperti dihantam hawa dingin. Apa yang dilakukan Zita di bumi saja menurut Rava sudah sangat menyeramkan. Bagaimana kalau lebih dari itu?
"Sepertinya, kita harus benar-benar membasminya." Ione menurunkan ponselnya dan menoleh kepada Lyra. "Lyra, menurutmu Lois mau tidak membantu kita melawan Zita?"
"Seharusnya sih dia mau. Dia kan sudah dipukuli sampai sekarat begitu. Dia juga ingin Zita binasa," jawab Lyra.
Mata Ione melirik Kacia, yang langsung menelan ludah. Melihat hal itu, Lyra pun mendesah, "Aku sudah mengenal Lois selama bertahun-tahun. Aku yakin, setelah semua yang telah terjadi, apalagi aku telah menolongnya dari kematian, dia tidak akan menyerang kita dari belakang. Dia itu tahu balas budi, kok."
Kacia sudah membuka mulutnya, tetapi langsung menutupnya lagi. Raut wajahnya lebih terlihat menunjukkan kekhawatiran dibandingkan amarah.
"Kalau kamu tidak setuju, lebih baik tidak usah ikut." Nada bicara Lyra terdengar begitu dingin.
Rava meringis. Dia mulai merasa tak nyaman dengan situasi ini.
"Oke, cukup. Tidak perlu diperpanjang lagi." Lois mengangkat kedua tangannya. "Kakak Stefan memberitahku kalau Lois tadinya mau bekerjasama dengan Medora untuk melawan Zita. Artinya, seperti kata Lyra, kalau untuk melawan Zita, Lois mau bekerjasama dengan siapa pun. Maaf Kacia, tapi kita kesampingkan dulu ...."
"Aku belum bilang tidak setuju, kok. Waktu dia ikut melawan monster besar itu, aku tidak bilang keberatan, kan?" ujar Kacia, meringis kaku.
"Tapi nada bicaramu .... Ehm ...." Lyra berdehem pelan. "Maaf .... Jadi, intinya kita akan bergabung untuk menghabisi Zita, kan?"
"Begitulah .... Barangkali kita bertiga sebenarnya sudah cukup, tetapi akan lebih aman kalau sekalian berempat. Sebenarnya, akan lebih baik lagi kalau berlima, tetapi sampai sekarang aku belum bisa menghubungi Ursa." terang Ione.
"Orangku sedang memeriksa lokasi mereka dengan melacak nomor handphone yang diberikan kepada kita," timpal Stefan, terdengar sedikit ketus.
Kening Ione langsung mengernyit. "Ada apa, Stefan? Kamu masih belum setuju kalau kita membunuh Zita?"
Beberapa saat berlalu, Stefan tak kunjung menjawab. Ia cuma menghela napas dan kembali fokus ke permainan di layar layar televisi.
"Kalau masih menghindar begitu, aku anggap saja kamu sudah setuju, ya?" lanjut Ione, sedikit tegas.
Rava menggaruk rambutnya. "Tapi, kita kan tidak tahu lokasi Zita di mana."
"Kalian bisa minta tolong kepadaku untuk meminta pihak atas agar mempertemukan kalian dengan ZIta," ujar satu sosok Piv yang kini berdiri di tengah-tengah mereka, tentu saja tanpa memberitahu terlebih dahulu.
"Apakah terlalu berlebihan kalau kami meminta waktu sampai Lois benar-benar sembuh?" tanya Ione dengan nada malas. "Dari reputasi pihak penyelenggara yang terkadang mempertemukan bidadari secara random, aku jadi sangsi mereka mau. Kerandoman adalah jalan ninja mereka. Bahkan menentukan peserta aja saking randomnya sampai psiko seperti Zita bisa masuk."
"Jalan ninja itu apa?" tanya Lyra dan Kacia serempak. Mereka pun saling bertukar pandang. Lyra langsung membuang muka dengan angkuh, sementara Kacia meringis kembali.
"Errr .... Nanti aku jelasin apa itu ninja .... Sekarang ada bahasan yang lebih penting." Sekarang Rava yang meringis.
"Permintaan kalian ini akan kuberitahu pihak atas terlebih dahulu," lanjut Piv. "Tapi, sepertinya mereka mau. Zita memang masuk kriteria pemilihan, tetapi bukan berarti pihak atas setuju kalau dia jadi ratu."
Ione menepuk kaki Rava. "Kalau kamu penasaran tentang penentuan pesertanya, lupakan saja. Mereka tidak akan menjawab kalau ditanya."
Ya, Rava memang penasaran mengapa orang seperti Zita bisa ikut pemilihan yang katanya dilaksanakan untuk menentukan pemimpin ini. Ia juga ingin tahu kriteria orang-orang yang dipilih menjadi tuan. Mengapa dirinya yang sangat tidak luar biasa ini juga ikut dimasukkan?
Namun, sedari dulu firasat Rava sudah berkata: Piv tak akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dari awal, Piv terkesan sangat tidak transparan.
"Jadi, sudah diputuskan, kan!?" Ione merentangkan kedua tangan. "Kita akan bergabung untuk membunuh Zita ...."
Tiba-tiba Stefan bangkit dari duduknya. "Maaf, aku pergi dulu. Aku nggak tahan mendengar kalian yang membahas pembunuhan dengan begitu santai."
"Stefan, kita ..... Hei, Stefan!" Ione menepuk keningnya begitu Stefan mulai melangkah pergu. Bidadari itu pun ikut bangkit dan langsung menyusul tuannya tersebut.
"Kalau kamu bagaimana, Kacia?" tanya Lyra, masih dengan nada dingin, kembali berkutat dengan ponselnya. "Apa kamu juga keberatan kalau kita membunuh orang gila itu?"
Kacia cuma bisa membisu. Rava makin tak nyaman dengan situasi yang ada.
Tak kunjung mendapat jawaban, Lyra pun beranjak dari tempat itu.
"Kalau kamu bagaimana Rava?" tanya Kacia setelah Lyra tak kelihatan.
Rava menghela napas panjang. "Sebelum ada solusi lain untuk menghentikan Zita, aku terpaksa ikut mereka."
"Begitu, ya." Kacia ikut menghela napas. "Sebenarnya, aku juga merasa ada yang mengganjal di hatiku. Aku belajar memanah dan bertempur untuk berburu dan mempertahankan diri, bukan membunuh orang."
"Yah, kalau dipikirin terus-terusan nggak bakal ada habisnya, sih." Rava menggaruk rambutnya, lantas menyodorkan satu stik konsol kepada Kacia. "Daripada ngomongin itu terus, g-gimana kalau kamu nemenin aku main .... Yah, i-itu kalau kamu mau, sih."
Kali ini Rava memaksa diri untuk menatap Kacia, walau dengan pipi yang merona merah. Bahkan Rava tidak mengerti mengapa dirinya ingin menghabiskan waktunya bersama Kacia sampai nekat mengajak bidadari itu bermain game.
Sempat terdiam, Kacia menerima stik itu. "Tapi, aku tidak pernah bermain permainan seperti ini."
"Aku ajarin!" Tanpa sengaja Rava mengeluarkan nada antusias.
***
Medora melongok ke kamar Gilang. Mendapati Gilang tengah menuliskan sesuatu di atas meja belajar dengan wajah murung, bidadari itu memajang senyum teduh andalannya.
"Gilang, makan, yuk. Dari tadi siang kamu belum makan, kan? Ibu udah masakin ayam goreng, loh."
Medora menghampiri si bocah cilik, mendapati kalau tuannya itu ternyata sedang tidak menulis di buku, tetapi menggambar beberapa wanita yang sedang mengelilingi monster gorila. Walaupun gambarnya jelek, Medora langsung tahu wanita-wanita itu adalah para bidadari, salah satunya dia sendiri, yang berambut ikal.
"Aku masih nggak ngerti, kenapa bidadari yang punya kekuatan super ada yang jahat begitu?" gumam Gilang dengan mata berkaca-kaca.
Melebarkan senyumnya, Medora berjongkok di samping tuannya itu. "Ini memang terdengar menyedihkan, Gilang. Tapi, orang biasa juga ada yang jahat, kan? Nah, bidadari itu sebenarnya sama saja dengan manusia. Ada yang baik ada yang jahat. Bedanya, bidadari itu memiliki kekuatan lebih."
Masih dengan wajah murung, Gilang menatap mata bidadarinya tersebut. "Kalau ketemu bidadari yang jahat lagi, apa Bu Dor bakalan melawannya?"
"Ibu sebenarnya nggak mau, tapi kalau nggak dilawan, mereka akan terus berbuat jahat." Medora mengusap pipi tuannya itu dengan lembut. "Jadi, ingatlah, Lang. Kalau Ibu melawan bidadari, sudah jelas mereka jahat. Kalau baik, Ibu jelas akan mengajak mereka bekerja sama. Kamu mengerti, kan?"
Perlu waktu beberapa saat sampai akhirnya Gilang mengangguk pelan. Medora sedikit mengacak rambut tuannya, kemudian bangkit berdiri. "Makan, yuk. Nanti ayam gorengnya keburu dingin .... Ibu suapin, deh."
"Beneran, Bu?" Walaupun sangat sedikit, ada pancaran kegembiraan di wajah Gilang.
Medora mengangguk mantap.