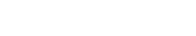54. Stefan
54. Stefan
"Mas, jangan lakuin ini, Mas," desak Rava dengan suara tertahan, teringat akan penderitaannya saat tak bisa lagi meraih mimpi.
Dengan kedua tangannya, Marcel memaksa kepala Stefan untuk menghadapnya. "Hei, hei .... Lihat mataku. Kamu harus memikirkan ini baik-baik, Stef."
Bibir dan tangan sang kakak bergetar sangat hebat. Ekspresi Marcel yang biasanya terlihat dingin, sekarang tergantikan oleh raut kekhawatiran tak terkira.
Stefan menurunkan tangan sang kakak, kemudian menghadap Piv kembali. "Apa yang harus kukasih? Harta? Semua ilmu yang kudapetin? Kepintaranku?"
"Jangan main-main, Stef!!!" Sekonyong-konyong, Marcel menarik kerah baju adiknya itu. "Masa depan kamu masih panjang! Jangan sia-siakan demi seorang cewek!"
Masih tak menatap kakaknya itu, Stefan malah melirik Ione, yang cuma bisa mengedikkan tangan. Mulutnya yang lebam tampak sedikit membuka dan menutup, tetapi tak ada ucapan yang bisa keluar dari sana.
"Kalau kak Anggun ada di posisi Ione, apa yang akan Kak Marcel lakukan?" desis Stefan.
"Jangan bawa-bawa Anggun, Stef," ujar Marcel dengan suara mirip menggeram. "Sebelum ini, kamu nggak pernah jatuh cinta, kan? Kamu itu belum punya pengalaman apa-apa .... Kamu nggak tahu apa-apa tentang cinta! Kamu .... Arggghhhh!!!"
Satu sosok Piv menggigit keras tangan Marcel, sementara satunya lagi yang entah muncul dari mana pun meloncat ke atas kepala Stefan. Hanya selang sedetik, Stefan sudah dikelilingi semacam energi pelindung berwarna kuning transparan. Mirip dengan bola pelindung Ione, tetapi bentuknya jauh lebih langsing, terlihat hanya cukup untuk satu orang.
Marcel mengibas-ngibaskan tangannya sampai Piv yang menggigitnya itu terlepas. Ia pun mengumpat karena tangannya berlumur darah.
"Maaf, Stefan," ucap Piv yang nangkring di kepala Stefan. "Semua yang kau sebutkan itu tidak cukup berharga bagi dirimu. Apa ada yang lain?"
Marcel memukul pelindung itu keras-keras dengan tangannya yang terluka. Noda darah pun sampai menghiasi pelindung tersebut. "Jangan, Stef! Aku mohon jangan! Kita akan cari cara agar Ione bisa tetap hidup!"
"Maaf, tapi pihak atas tidak akan membiarkan kalian membawa bidadari ke rumah sakit atau semacamnya," timpal Piv yang tadi menggigit Marcel, berbicara dengan mulut penuh darah. "Konsekuensinya nanti ...."
"Diam kamu makhluk laknat!" hardik Marcel.
Stefan kembali melirik Ione, yang kini tak memberikan respon apa pun. Hanya dadanya saja yang naik turun, tanda bidadari itu masih bernapas, walaupun kemungkinan besar sudah tak sadarkan diri.
"Ternyata, Kakak perhatian juga sama aku. Kakak mengkhawatirkan aku di saat seperti ini." Akhirnya, Stefan menatap kakaknya, lantas memajang senyum samar. "Maaf, tapi keputusanku sudah bulat, Kak. Ione sudah mengisi hari-hariku yang hampa. Aku nggak bisa hidup tanpanya, Kak."
Marcel melorot dan sampai bersimpuh di lantai, menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca dan mulut menganga. Dia sudah tak bisa melakukan apa pun.
Tubuh dan hati Rava bergetar hebat. Dirinya pun tak bisa melakukan apa pun dan dia sangat membenci hal itu.
Stefan menghela napas panjang. Ekspresinya kini jauh lebih tenang. Senyumnya semakin mengembang. "Dari semua indraku, mana yang paling pantas untuk dikorbankan, Piv?"
"Stefan!!!" hardik Marcel lagi. "Jangan, Stefan!"
Piv membisu sejenak. "Mata."
"Baik, ambil penglihatanku," desah Stefan ringan, seolah apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat biasa.
Keheningan pekat seketika menyelimuti ruangan itu. Rava merasakan sekujur tubuhnya bak dialiri hawa dingin.
"Baiklah, Ione akan kami ambil dulu," tutur Piv yang tadi menggigit Marcel, kemudian berpindah ke dekat ujung kepala Ione.
Perlahan, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar. Sangat lebar, sampai besarnya benar-benar tidak bisa dinalar.
Melihat kegelapan pekat dari mulut itu, Rava merasa perutnya bergejolak, memicu mual di kerongkongannya. Ia teringat adegan ketika Xi—bidadari berbaju merah marun itu—ditelan oleh Piv. Sebuah peristiwa yang menghantui mimpinya sampai berhari-hari.
Tak tahan lagi, Rava buru-buru pergi dari tempat itu, tepat ketika Piv sudah mulai menelan kepala Ione.
"Rava, kamu mau ke mana?" tanya Kacia saat Rava sudah ada di luar kamar.
"Itu ...." Rava menelan ludah. "Maaf, tapi aku lagi pengen sendiri, Kacia."
Setelah berkata seperti itu, Rava melanjutkan langkahnya.
***
Menempati kursi taman di pelataran belakang rumah Stefan, Rava membungkuk dan meremas kepalanya. Semakin hari, keadaan semakin buruk saja. Jangankan untuk mengumpulkan bidadari lain demi menyelesaikan pertarungan absurd ini, sekarang malah Stefan harus berkorban besar.
"Rava? Kamu di situ?"
Rava tersentak mendengar suara Stefan itu. Begitu mendongak, Rava mendapati Stefan yang sedang dituntun ajudannya, Herman. Rava langsung tahu kalau ada yang tidak beres. Mata Stefan jelas-jelas tidak tertuju kepadanya.
"Pak Herman, tolong tinggalkan kami sebentar," lirih Stefan.
Sang ajudan pun menangis sesenggukan, kemudian bertolak dari tempat itu.
Rava tak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Setelah Herman tak terlihat, ia pun berkata dengan urat-urat wajah yang menegang, "Kenapa, Mas? Kenapa Mas Stefan melakukan itu?"
"Seharusnya kamu yang paling mengerti, Rava. Kamu itu yang lebih dulu melakukan hal seperti ini."
Rava mengusap wajahnya gusar. "Tapi, Mas kan sudah lihat aku sebagai contohnya. Mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dari diri kita itu akan memberikan dampak besar, Mas. Aku benar—benar merasa ada yang hilang dari diriku."
"Cuma satu kali aku mendengar kamu berapi-api seperti ini, waktu kamu marah dengan Fino, tuan Kacia yang dulu." Stefan tertawa getir. "Sekarang, kamu marah sama aku?"
"Setelah melakukan pengorbanan itu, aku merasa nggak utuh lagi dan itu sangat menyiksaku, Mas. Mas Stefan seharusnya tahu dengan melihatku yang menderita begini," tegas Rava, nada bicaranya semakin tinggi.
"Aku melihat kamu baik-baik saja, kok. Kamu bisa melalui semuanya dengan baik. Kalau kamu bisa melakukannya padahal yang kamu korbankan itu sebuah mimpi, maka apalah aku, yang cuma mengorbankan satu indra saja?"
Rava kehabisan kata-kata. Ia cuma bisa memandangi mata Stefan dengan mulut menganga. Mata itu yang kosong tanpa adanya cahaya kehidupan.
"Ah, barangkali sebenarnya kamu nggak akan mengerti. Kamu masih punya ibu yang menyayangi kamu. Singkatnya, walaupun kamu hampir nggak pernah keluar dari kamar, hidupmu jauh lebih baik dari aku." Stefan mengembangkan senyum samar. "Sementara aku? Rumah besar, pendidikan tinggi, teman dan bahkan keluargaku itu tak ada artinya bagiku. Ayah dan kakakku itu bagaikan orang asing. Bahkan sekedar menyapa nggak pernah kami lakukan, Rav. Aku juga menjalani kehidupan tanpa tujuan, tanpa ambisi."
Rava masih tak bisa berkata-kata.
"Sampai akhirnya, Ione datang di kehidupanku," lanjut Stefan, terdiam sejenak. "Aku tahu, dia tulus memperhatikan diriku ...."
"Aku sama sekali nggak ngerti apa yang Mas bicarakan," potong Rava akhirnya, menunduk dan mengepalkan kedua tangan.
"Bohong. Kamu pasti mengerti apa maksudku." Bibir Stefan mulai bergetar. "Kamu nggak sebodoh itu. Kamu mengerti, tapi nggak mau mengakuinya."
Kembali terdiam, Rava bangkit dari kursi, kemudian mulai terhuyung meninggalkan tempat itu.
"Kalau ternyata kamu memang benar-benar bodoh dan nggak mengerti, maka dengarkan ini baik-baik: aku cuma mau menyelamatkan orang yang paling berharga bagiku, Rav."
Mulut Rava masih tak mengeluarkan suara. Bunyi yang terdengar di tempat itu hanyalah langkah kaki Rava yang terus menjauh.