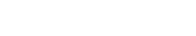76. Menjadi Kenangan
76. Menjadi Kenangan
Kemudian, Medora mendatangi kamar tuannya dengan langkah terpincang. Setibanya mereka di rumah beberapa saat yang lalu, Gilang langsung mengurung diri di kamar.
Setiap gerakan yang dilakukannya, Medora merintih. Semua sendinya seperti mau copot dan luka-luka di tubuhnya terasa begitu menyengat. Rangkaian perban yang dia bebatkan sendiri di tubuhnya itu sama sekali tak membantu.
Menghela napas, ia pun mengetuk pintu kamar Gilang. "Gilang, ini Bu Dor, Lang. Bu Dor boleh masuk, nggak?"
Medora mencoba membuka pintu tersebut, tetapi Gilang sudah menggerendelnya dari dalam.
"Ibu minta maaf. Mungkin ibu memang salah. Tapi, percayalah, Lang. Itu ibu lakukan bukan tanpa alasan," desah Medora, kembali menghela napas.
Gilang masih tak menjawab. Medora pun bersimpuh di hadapan pintu kamar tuannya itu. "Ibu bakal tetap duduk di sini sampai kamu mau keluar."
Medora sangat membutuhkan pasokan energi kehidupan dari Gilang untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Idealnya, dia berada di dekat Gilang, supaya penyerapan energi kehidupan itu makin maksimal. Akan tetapi, sekarang hanya inilah yang bisa dia lakukan. Dia tidak tahu dampak apa yang akan terjadi bila dirinya mendobrak pintu itu. Kalau sampai Gilang trauma dan tak mau menjadi tuannya, dia juga yang repot.
Untuk kesekian kalinya, Medora mengutuk tuannya itu dalam hati.
"Apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Dirga, baru muncul di rumah, masih mengenakan jaket ojolnya.
"Gilang nggak mau keluar," jawab Medora lirih, sebenarnya sudah tahu kedatangan pria itu.
Dirga berdecak, melipat tangan di dada. "Kok, bisa? Kamu kan yang terus bersamanya? Apa yang kamu lakukan sampai membuatnya seperti itu?"
Mendengar nada sinis dari ayah Gilang itu, Medora merasakan emosinya menggelegak. "Apa kamu menyalahkan aku, Dirga?"
"Memangnya siapa lagi? Kamu yang mengurusinya dari pagi sampai malam, kamu bertanggung-jawab ...."
"Aku? Bertanggung-jawab?" Medora tertawa getir, bangkit dari lantai. "Aku, yang orang asing ini? Lalu, kamu mengganggap dirimu tidak bertanggung-jawab kepadanya? Bukannya kamu ini orangtuanya?"
"Aku kan sibuk bekerja ...."
"Dan setelah bekerja, kamu cuma duduk-duduk santai menonton televisi sambil merokok," potong Medora, menjaga suaranya agar tidak meledak, demi menjaga perasaan Gilang. "Kamu tidak pernah bertanya bagaimana sekolah Gilang, mengajaknya bermain walau sejenak .... Ah, waktu berangkat sekolah juga kamu cuma menyapa Gilang sekedarnya saja. Kamu tidak pernah memperhatikannya dan sekarang kamu malah menyalahkanku yang mengurusnya? Aku ini tidak dibayar, Dirga. Seharunya kamu bersyukur ada yang mau memerhatikan anakmu."
Dirga hanya bisa terdiam dan membuang muka.
"Aku tahu, mungkin kami capek, tapi Gilang itu anakmu, Dirga." lanjut Medora, menekan jari telunjuknya ke dada pria itu. "Apa pun yang terjadi, kamulah yang paling wajib memerhatikannya."
Setelah beberapa menit tak kunjung mendapat tanggapan dari Dirga, Medora memijati keningnya. Bidadari itu sudah terlalu lelah. Walau Varya yang dianggapnya sebagai penghalang utama sudah tiada, Medora merasa tujuannya justru semakin jauh saja. Ya, kalau tuannya tidak mau bekerjasama seperti ini, bagaimana bisa dirinya memenangi pemilihan ratu?
"Tapi, tidak bisa dipungkiri juga kalau akulah yang membuat Gilang jadi seperti ini." Medora mundur sambil tersenyum pahit. "Baiklah, aku akan bertanggung-jawab."
Medora mengetuk pintu kamar tuannya itu kembali. "Lang, keluar, Lang. Kalau nggak mau keluar, Ibu pergi aja ya? Nggak usah balik lagi."
Terdengar derit keras dari dipan di dalam kamar. Tak perlu waktu lama sampai Gilang membukakan pintu. Dengan mata sembab, ia memandang bidadarinya itu dengan ekspresi wajah tak percaya.
Medora merentangkan senyum teduh andalannya. Tak seperti biasanya, kali ini dia justru melakukannya dengan lebih ringan. Kesabarannya sudah habis. Dia tak peduli lagi dengan masalah menjaga mental bocah cilik ini.
"Sekarang, Gilang nurut aja apa kata Bu Dor, ya. Nggak usah nanya ini-itu juga kalau Ibu melakukan sesuatu. Kamu tinggal ikut saja." Medora berlutut, mengusap lembut kepala tuannya itu. "Kalau nggak, Ibu beneran bakalan pergi."
Meski kata-kata Medora itu terdengar lembut, tetapi sudah cukup untuk membuat mata Gilang membelalak.
"Ibu harap, kamu mengerti, ya." Medora pun memeluk erat tubuh bocah cilik itu, melirik Dirga yang masih saja berdiri diam.
***
Senja telah menjelang. Rava dan kawan-kawannya berkumpul di rumah yang menjadi tempat persembunyian istri Bagas. Dengan kondisi luka-luka seperti itu, para bidadari tak mungkin kembali ke rumah kontrakan yang biasa. Bisa-bisa ibu Rava menaruh curiga.
Candra sudah dikembalikan ke rumahnya, sementara anak kecil yang diselamatkan Varya sedang diurus Herman untuk dibawa kepada kerabat.
Sejak tadi datang ke rumah itu, membalut luka-luka, sampai berkumpul di ruang tamu itu, mereka terus membisu.
"Kira-kira, berapa korban yang akan jatuh setelah ini, ya?" gumam Ione dengan nada bicara sedikit parau.
"Tidak ada gunanya membahas hal itu," timpal Stefan pelan. "Kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan."
"Tapi .... Ah ...." Ione pun akhirnya memutuskan untuk menahan diri.
Rava tidak sanggup membayangkannya. Atau lebih tepatnya, tidak mau membayangkan banyaknya korban yang mungkin jatuh karena gelombang monster itu. Jelas tak mungkin sedikit. Gelombang pertama saja sudah cukup banyak menumpahkan darah.
"Aku harus pulang. Hari ini kita nggak jualan dan nggak ngasih kabar. Ibuku pasti kebingungan. Aku bakal ngejelasin. Sebenernya bisa lewat hape, tapi kalau ngelihat aku secara langsung, paling nggak ibuku bakal lebih tenang dan nggak menduga-duga." Sedikit menggelengkan kepala, Rava bangkit dari duduknya. "Kacia sama Lyra di sini aja. Ibuku bisa kaget kalau ngelihat luka kalian. Nanti, aku bakal cari alasan buat balik ke sini lagi."
"Biar aku bantu jelasinnya," timpal Stefan.
"Nggak usah, Mas. Lebih baik Mas fokus nyembuhin Ione." Rava beralasan. Sebenarnya, dia ingin sendiri dulu untuk menenangkan hatinya. "Kalau gitu, aku pamit dulu."
Lyra menghela napas. "Sebenarnya aku mau melarang. Monster-monster itu mungkin masih berkeliaran. Tapi, kasihan bu Sinta kalau tidak diberi kabar."
"Hati-hati, Rav." Kacia memandangi tuannya itu dengan wajah cemas.
"Kalau ada apa-apa, segera hubungi kami," imbuh Lyra.
"Aah ... Iya .... Tenang aja, rumahnya kan nggak terlalu jauh," jawab Rava, kemudian keluar dari rumah.
Marcel mengusap wajahnya. "Lebih baik kita juga pulang, Lois. Nggak ada gunanya kita .... Lois?"
Kening Marcel mengerut. Lois kini menunduk. Air matanya kembali menetes dan tubuhnya bergetar lagi. Bukannya menjawab tuannya, bidadari itu malah berlari ke bagian dalam rumah.
Lyra langsung bangkit, memberi isyarat tangan agar yang lain tetap duduk, kemudian menyusul saudari angkatnya itu. Mencari-cari sejenak, ia pun menemukan Lois di halaman belakang, tengah meringkuk di tanah sambil bersandar di tembok.
"Kamu tahu apa yang nona Varya ceritakan padaku, Lyra?" rintih Lois, memandang ke arah lain dengan air mata yang turun makin deras. "Dia itu rela melacurkan diri untuk mencapai tujuannya yang mulia. Bayangkan, dia mau berhubungan badan dengan pejabat hidung belang .... Nona Varya melakukannya agar pejabat itu menyampaikan usulannya tentang penambahan persenjataan pasukan ke dewan."
Mulut Lyra sedikit membuka. Dia sudah akan menanggapi, tetapi memilih untuk membiarkan saudari angkatnya itu melanjutkan cerita.
"Dia adalah salah satu bidadari terbaik yang pernah kutemui .... Dan sekarang dia telah tiada, hanya karena aku .... Hanya karena aku ...." Lois tercekat hebat.
Lyra memejamkan mata, menarik napas panjang. Tubuhnya pun mulai bergetar. "Karena kamu ingin menyelamatkan aku, kan?"
Isakan Lois pun pecah. "Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli dengan pemilihan ratu ini. Keluargaku tak pantas diselamatkan dan aku tak tahu apa yang akan kulakukan kalau sudah menjadi ratu. Jadi, waktu dikirim ke sini, aku hanya mengikuti arus saja .... Aku hanya menjalankan aturan main, tanpa punya tujuan pasti .... Sampai akhirnya, aku bertemu denganmu lagi setelah bertahun-tahun."
Lois tak sanggup berbicara lagi. Ia memeluk kakinya dan membenamkan mukanya ke lutut.
Lyra pun sedikit menarik napas, mulai mendendangkan sebuah nyanyian. Suara merdunya yang mendayu-dayu pun menggema indah.
Ia membawakan balada yang bercerita tentang seorang pahlawan. Pahlawan yang selalu berjuang untuk kebajikan. Meski harus menemui berbagai rintangan, pahlawan itu terus maju. Kendati tubuhnya remuk redam, dia tetap berjuang.
Nyanyian bidadari itu menggapai ruang tamu yang masih ditempati Ione, Kacia, Stefan, dan Marcel. Kendati nyanyian itu dibawakan dengan bahasa yang sangat asing, Stefan bisa merasakan getaran hebat di hatinya.
"Ini adalah nyanyian yang biasanya dibawakan di pemakaman para pahlawan yang gugur," terang Kacia, mulai terisak.
"Tapi, ini bukan nyanyian yang sedih." Ione memunculkan serulingnya, kemudian memajang senyum lebar. "Ini adalah lagu perayaan karena kita pernah memiliki sang pahlawan."
Dengan tangan bergetar, Ione mulai meniup serulingnya, mengikuti nyanyian yang dibawakan Lyra.