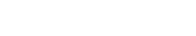63. Sesal
63. Sesal
"Silahkan masuk, Bu," ucap Herman kepada Dini, istri Bagas yang masih duduk di mobil.
Menyeka sisa air matanya, Dini turun dengan dibantu Herman. Sembari menggendong putrinya yang kini tertidur, ia memandang rumah sederhana itu sejenak, kemudian menoleh kepada para bidadari yang ada di halaman. "Suami saya mana?"
Para bidadari dan Rava tak berani menatap wajah Dini. Mata Dini pun perlahan membelalak. Mulutnya juga membuka lebar. Satu demi satu tetesan air matanya kembali turun.
"Ooh, mas Bagas ...." Dini menahan diri agar tangisnya tidak terlalu keras, supaya putri di pelukannya itu tidak terbangun. "Mas Bagas ...."
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan suami Bu Dini," ujar Stefan dengan nada serius, tetapi tetap terdengar lembut. "Sekarang, Ibu istirahat saja dulu. Kalau butuh sesuatu, tinggal bilang ke pak Herman. Pakaian, susu, peralatan mandi, atau yang lainnya, semua yang ibu butuhkan akan kami sediakan."
"Benar sekali, Bu Dini tinggal bilang saja," imbuh Herman.
"Terimakasih banyak, padahal kalian nggak mengenal keluarga kami," timpal Dini dengan suara parau.
Mereka pun memasuki rumah itu. Rava melirik Kacia, yang matanya masih diselimuti cairan bening. Tubuh bidadari mungil itu juga masih bergetar.
Sementara Herman mengantarkan Dini dan putrinya menuju kamar, yang lain berkumpul di ruang depan. Semuanya duduk di sofa dan menutup mulut, memicu atmosfer yang terasa tak nyaman bagi Rava.
Sampai akhirnya, Lyra berdiri dari, menghampiri Kacia dan menarik kerah baju bidadari bertubuh mungil itu.
"Kamu tahu kan apa salahmu, Kacia?" desis Lyra, dengan bibir bergetar dan tatapan mata yang semakin tajam.
Akhirnya, air mata Kacia mengalir kembali. "M-maaf ...."
Tiba-tiba saja, Rava memisahkan tangan Lyra dari kerah baju Kacia. Pemuda itu balas menatap tajam Lyra.
"Hooo .... Kamu mau membelanya, Rava?" Suara Lyra terdengar begitu sinis. "Walaupun jelas-jelas perbuatannya itu salah?"
Urat di wajah Rava mulai menegang. "Kacia itu nggak pengen jadi petarung seperti kamu atau Lois. Dia belajar memanah dan bertempur untuk berburu dan membela diri. Dia juga terpaksa datang ke sini. Dia nggak punya keinginan mengikuti pemilihan ratu yang bodoh ini. Jadi, jangan salahkan dia. Jangan paksa dia melakukan sesuatu yang nggak pernah diajarkan padanya."
Lyra berkacak pinggang, menghela napas begitu panjang. "Tapi, dia seharusnya tahu situasi. Dia harusnya menyadari, kesempatan emas itu akan bisa menyelamatkan orang lebih banyak."
"Ah, kalau mau bicara kesalahan, kamu juga punya, Lyra." Nada bicara Rava agak meninggi. "Kalau saja dari awal kamu menggunakan kekuatan pedang cahayamu sesuai saranku, energi pelindung di tubuh Zita akan lebih cepat habis. Jadinya, Ione bisa mengeksekusi Zita."
Decak kecil meluncur dari mulut Lyra. Bidadari itu pun mendekatkan wajahnya ke muka tuannya itu. "Kamu tahu apa tentang strategi? Aku menyimpan kekuatan itu untuk saat-saat krusial dan tak terduga. Kamu ini cuma mengurung diri di ...."
"Sebaiknya kalian pulang," ucap Stefan tiba-tiba, dengan suara agak keras menyela ucapan Lyra. "Nanti ibunya Rava khawatir kalau kalian nggak pulang-pulang. Aku sama Ione bakal di sini buat ngejagain bu Dini sama anaknya."
Ione menghela napas. "Aku setuju, sih. Kita juga sudah capek."
Lyra menyipitkan matanya, kemudian pergi begitu saja dengan langkah tegas. Sementara itu, Kacia mulai menangis sesenggukan, dan Ione pun mendatanginya, memberikan belaian lembut di punggung bidadari bertubuh mungil itu.
Rava pun diam membisu, tak mengerti mengapa dirinya bisa mengungkapkan isi hatinya seperti itu, bahkan nyaris dengan menjerit.
***
Menemukan Kacia tengah duduk merenung di atap rumah kontrakan, Rava berinisiatif untuk mengambil tangga bambu yang tergeletak di pelataran belakang.
"Eeh?" Kacia terkejut saat ujung tangga itu menempel di pinggiran atap. "Biar aku saja yang membawa kamu ...."
Kacia tercekat. Rava pun langsung mengalihkan mukanya yang kini dihantam panas. Pemuda itu tent saha ingat saat-saat dirinya dibopong bak putri ke atas atap.
"A-aku bisa sendiri, kok." Akhirnya, Rava mulai menaiki tangga itu. Begitu mencapai puncak, ia pun dibantu oleh Kacia. Aneh, menggenggam tangan Kacia saja bisa membuat wajah Rava terasa semakin memanas. Rava tak mengerti, bukannya dia sudah cukup lama bersama bidadarinya itu?
Krak!
"Uwaaaa!!!"
"Ravaaaa!!!" Kacia ikut memekik.
Karena sudah lapuk, pijakan tangga yang diinjak Rava pun patah. Rava langsung bergerak-gerak panik, membuat tangga itu rubuh. Untungnya, Kacia bisa menahan tubuh Rava.
"Bikin kaget saja." Menghela napas, Kacia pun menarik tubuh Rava dengan mudahnya.
Rava pun berbaring di atap dengan napas ngos-ngosan. Barusan, dia merasa hampir mati.
Mendengar hal itu, Lyra pun keluar lewat pintu belakang, hendak memeriksa apa yang terjadi. Namun, begitu melihat Kacia dan Rava di atas atap, dia kembali masuk dengan ekspresi yang seperti biasanya, sama sekali tak berubah.
Kacia dan Rava yang mengetahui hal itu tak sanggup memberi tanggapan apa pun.
"Hari yang berat, eh?" celetuk Rava setelah beberapa saat mengatur napas, kemudian duduk di samping bidadarinya itu.
Kacia memeluk lututnya. Matanya yang sembab tertuju lurus ke depan. Dia membisu dengan kedua ujung bibir yang turun untuk beberapa detik, sebelum akhirnya berucap lemah, "Terimakasih sudah membelaku, Rav. Tapi, kesalahan tetap ada padaku. Aku yang seharusnya menghabisi Zita. Aku menyia-nyiakan kesempatan itu."
"Yah, tidak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan orang lain," timpal Rava pelan. Kali ini dia sudah mempersiapkan kalimat yang akan diutarakannya. "Barangkali, Ione atau Lyra bisa membunuh, tetapi kamu dan aku nggak bisa melakukannya. Terutama aku, yang nggak pernah latihan bertarung sama sekali. Bertarungnya cuma lewat game aja."
"Kamu bisa melakukannya, Rav," desah Kacia, kini mendongak ke arah langit mendung tanpa bintang. "Aku melihat di matamu waktu kamu memukul kepala Zita .... Ah, aku tidak bilang kamu ini bisa menjadi pembunuh. Bukan itu maksudku." Kacia meringis canggung seperti biasanya.
Rava tak bisa berkata-kata. Kalimat terakhir Kacia itu sedikit memicu lonjakan di jantungnya. Dirinya bisa membunuh? Benarkah itu? Kalau diberi kekuatan, dia akan bisa mencabut nyawa seseorang? Dirinya? Dengan kedua tangannya ini?
"Ah, lupakan kata-kataku itu, Rav. Aku minta maaf." Kacia sedikit memijat keningnya.
Rava menggeleng pelan, berusaha tak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan liar yang mulai menghinggapi kepalanya. "Nggak apa-apa, kok .... Ah, seperti yang Ione pernah bilang, kita hanya bisa melakukan apa yang terbaik. Kalau boleh kutambah sedikit, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dalam hal yang bisa kita lakukan."
Perlahan, Kacia menoleh kepada tuannya itu. Bibirnya mulai membentuk senyum yang sangat tipis. "Terimakasih, Rav. Keberadaan kamu di sini sudah sangat membantuku."
Pandangan Rava terfokus kepada wajah bidadarinya itu. Senyum itu seakan membangkitkan hangat di dada Rava. Ia ingin waktu berhenti, supaya senyum itu bisa terus bertahan.