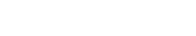Bab 6
Bab 6
"Romo sepertinya salah paham, Arni ndhak pernah menggoda aku, Romo. Kami hanyalah kawan," kubilang. Tapi, Romo Nathan tampak tak percaya. Mata kecilnya itu memicing sebelah, memandangku dengan tatapan bak elang.
"Kawan kamu bilang?" katanya dengan senyuman miring yang sudah jelas itu bukanlah sebuah senyuman yang baik. "Kawan apa? Kawan kelon atau kawan di atas ranjang? Memalukan!" sentaknya sambil menebas surjan. Rasanya, napasku tiba-tiba berhenti begitu saja mendengar Romo mengatakan hal itu. "Ndhak ada cerita di buku mana pun, ndhak ada catatannya di kamus mana pun, jika seorang lelaki lajang bisa berkawan dengan perempuan yang sudah bersuami, mengerti!"
"Tapi, Romo... pun dengan buku dan kamus, ndhak ada juga di keduanya yang melarang itu."
"Cukup, Arjuna!" bentak Romo yang berhasil membuatku terdiam. Dia menempelkan jari telinjuknya ke arahku, dengan wajah merah padam. "Jangan suka membantah seperti biungmu."
"Maaf, Juragan Nathan, jikalau kehadiran saya ini membuat runyam," kata Arni menengahi. "Tapi jujur, sungguh, ndhak pernah terbesit sedikit pun di pikiran saya untuk menggoda Juragan Arjuna. Saya cukup tahu diri untuk itu. Jadi, Juragan Nathan ndhak perlu cemas akan hal itu."
"Jika kamu tahu diri, seharusnya kamu ndhak mendekat dan seolah-olah memberi harapan kepada putraku, kan? Dasar, perempuan rendah ndhak tahu tata krama. Kamu tahu jika bercakap dengan lelaki yang bukan suami atau saudaramu hendaknya kamu mengajak kawan? Bukan malah berduaan seolah-olah kamu ingin menggoda. Ingat, Arjuna ini seorang Juragan. Bahkan seorang lelaki yang ingin menghadap saja harus memiliki tata krama, ndhak sepertimu. Bodoh dipelihara,"
Setelah mengatakan itu, Romo langsung pergi. Tapi kemudian, langkahnya terhenti sembari menoleh ke arahku. "Masih betah berdiri di situ, Arjuna? Ndhak mau pulang?" katanya.
"Tapi, pekerja kebun belum pulang, Romo. Masih ada--"
"Halah, jangan banyak alasan. Romo juga pernah muda sepertimu. Cepat, pulang!"
Aku segera melangkah mengikuti Romo. Tapi ndhak tega juga meninggalkan Arni sendirian setelah tamparan-tamparan yang diberikan oleh Romo. Bagi perempuan, itu benar-benar sangat memalukan. Mataku menangkap krisan yang ndhak jauh dari tempatku berdiri, segera kuhampiri lagi Arni yang sudah hendak pergi. Kugenggam pundaknya, membuat langkahnya terhenti kemudian ia pun menoleh. Kemudian, kuserahkan krisan itu seraya berkata, "bunga krisan yang cantik ini untukmu, sebagai penawar luka dariku."
Setelah ia menerima bunga itu aku cepat-cepat pergi, setengah berlari kukejar langkah Romo. Aku pun ndhak bisa melihat bagaimana tanggapan Arni mengenai ini. Apakah pipinya akan merona ataukah dia akan biasa saja? Jujur, aku penasaran. Dan yang lebih membuatku penasaran adalah, sejak kapan aku bisa berkata semanis itu dengan perempuan? Padahal, Romo dan Biung ndhak pernah mengajari itu.
*****
Sore ini aku duduk di pelataran rumah bersama dengan Paklik Sobirin. Kami baru saja pulang dari Berjo untuk menilik beberapa lahan sewaan yang ada di sana. Ada beberapa lahan yang gagal panen, dikarenakan buah-buah mentimunnya busuk atau bahkan yang paling parah, daun-daun pohon yang mau berbunga habis dimakan ulat. Entah, rugi berapa saja itu, aku ndhak tahu. Sudah kali ke dua di tahun ini kebun yang kuolah di sana selalu gagal. Entah kenapa, atau aku memang ndhak bisa.
"Ndhak akan mengepul ini asap dapur para istri yang ada di Berjo. Semuanya ludes. Mentimun puluhan hektar ludes," kata Paklik Junet yang baru saja datang. Ia kemudian duduk bersamaku juga Paklik Sobirin. "Kamu, sih, Jun.... susah kukasih tahu, lebih baik tanami saja tembakau. Tapi kamu ngeyel. Sekarang, rugi berapa saja kita ini," tambahnya menyalahkanku.
Kulihat Paklik Sobirin tampak menempeleng Paklik Junet, kemudian ia berdehem beberapa kali.
"Kamu ini, lho, Net. Ndhak tahu diri," katanya. "Meski kamu adalah Paklik dari Juragan Arjuna, tapi biar bagaimanapun, kamu hanyalah seorang abi dalem. Pantang bagi seorang abdi dalem bertindak kurang ajar seperti itu. Apalagi menyalahkan Juragan seolah-olah abdi dalemlah yang paling benar."
"Sudah, Paklik, aku ndhak apa-apa." kubilang. Ndhak enak juga jika mereka harus bertengkar hanya karenaku.
"Lho, ini masalah serius, lho, Juragan. Bahkan abdi dalem yang paling dihormati oleh Juragan Adrian dan Juragan Nathan pun, ndhak pernah melakukan hal itu. Hey, Junet... kamu tahu Paklik Marji?" kata Paklik Sobirin yang kini bertanya kepada Paklik Junet. Paklik Junet mengangguk, tanpa bersuara. "Beliau itu adalah contoh abdi dalem yang paling setia di muka bumi ini. Meskipun beliau tahu jika kedua Juragan tersohor di negeri ini menganggapnya sebagai Romo, tapi ndhak pernah sedikit pun terlintas dalam benaknya untuk menggurui kedua Juragan kita, apalagi menyalahkan sepertimu. Beliau selalu setia mendampingi juragannya, apa pun itu yang terjadi. Bahkan, beliau rela mati untuk juragannya. Lalu kamu, apa kamu rela mati untuk juraganmu lebih-lebih juraganmu adalah keponakanmu sendiri?" lagi, Paklik Junet terdiam, dan itu berhasil membuat Paklik Sobirin tertawa. " Ndhak bisa jawab, toh? Ya memang seperti itu kelakuan para bawahan zaman sekarang ini. Kesetiaan menjadi hal kesekian yang diutamakan."
"Lho, kok malah merembet-rembet itu, lho," kata Paklik Junet pada akhirnya. "Aku, kan, hanya membahas mentimun, toh."
"Lha, kamu sendiri, bicaranya seperti itu. Menyalahkan Juragan Arjuna."
"Sudah, sudah... ada apa, toh, ini kok ribut-ribut. Mbok ya yang rukun. Sesama abdi dalem itu harus kompak, lho." Bulek Sari datang, menengahi. Ia membawa wedang jahe beserta putu ayu. Untung Bulek Sari datang, kalau endhak pastilah dua laki-laki ini akan perang nanti.
"Oh, ya, Bulek, di mana Manis? Sudah hampir seminggu aku ndhak melihatnya. Kok ya rindu," kutanya. Bulek Sari tampak terkejut, dan aku ndhak tahu, kenapa ia harus terkejut dengan pertanyaan sederhanaku itu.
"Tumben rindu Manis? Ndhak rindu perempuan yang sudah menjadi istri orang itu?" ledek Paklik Junet.
"Siapa?" tanya Paklik Sobirin penasaran juga. Kulirik Paklik Junet, ia malah tertawa.
"Itu, Arni... bahkan kisah cintanya di kebun teh kemarin, yang dimarahi Juragan Nathan sudah tersebar luas di kampung ini."
Tuhan, bisa ndhak bungkam mulut laki-laki lamis ini untuk selamanya. Sepertinya, ia bahagia benar melihatku ndhak punya muka di depan orang-orang.
"Bulik, bagaimana kabar Manis?" tanyaku lagi, mengabaikan ucapan Paklik Junet.
"Manis, Manis ke kota, Juragan...," jawab Bulik Sari pada akhirnya. "Bapaknya harus dirawat di rumah sakit, dan di rumah sakit kotalah yang memiliki peralatan medis yang memadai. Jadi, mau ndhak mau Manis harus ke sana demi bapaknya."
Bapak yang dimaksud Bulik Sari bukanlah Bapak kandung Manis, sebab kedua orangtuanya sudah lama ndhak ada. Dia--Bapak yang disebut oleh manis adalah, pakliknya yang ndhak lain merupakan adik kedua dari Bulik Sari. Yang kebetulan ndhak memiliki istri. Dia tinggal bersama Manis dan emaknya--Simbah Manis, yang sudah menganggap Manis seperti anak kandungnya sendiri.
"Lalu, dari mana Manis mendapatkan biaya ke rumah sakit, Bulik?" kutanya, sebab aku tahu jika Manis sedang kesusahan sekarang. Bukan... bukan hanya sekarang, tapi sedari lama.
Bulik Sari tampak risau mendengar pertanyaanku itu. Sedikit hati-hati ia memandangku kemudian menundukkan pandangannya lagi seraya berkata, "urusan biaya, sudah... sudah ada yang membantu, Juragan. Jagabaya kampung sudah membantu."
Jagabaya kampung? Duda beranak empat itu? Kurasa hubungan keluarga mereka ndhak sedekat itu untuk sekadar membantu. Bukankah seharusnya aku yang paling berhak membantu Manis? Bukan jagabaya sialan itu. Belum sempat kulontarkan pertanyaan lagi, Bulik Sari buru-buru pergi. Aku yakin, ia sengaja menghindar. Dan aku lebih yakin jika ada hal yang ndhak beres di sini.
*****
Pagi ini, aku sudah duduk di atas motor kesayanganku, bertempat di parkiran pasar kampung Berjo. Pasar di sini terbilang ramai, bahkan hampir sama ramainya dengan pasar yang ada di kecamatan. Itu sebabnya, mungkin, pasar ini hendak dipindah. Atau malah dihilangkan. Dan aku ndhak tahu apa penyebabnya. Siapa peduli.
Sebenarnya, enggan benar aku pergi ke pasar. Kalau bukan Biung yang terus memaksa untuk kuantar. Sebab katanya, kalau ada Dik Rianti, Biung selalu ditemani oleh anak perempuan kesayangannya itu. Omong-omong soal Di Rianti, bocah tengil itu tampaknya betah benar berada di Jakarta. Padahal Romo dan Biung sudah beberapa kali kirim kabar dan menyuruh untuk pulang ke kampung, tapi diabaikan. Lihat saja nanti kalau pulang, akan kubuat dia menangis sebab telah membuat kangmasnya kerepotan.
"Lihatlah perempuan ayu itu, Arni...," kudengar samar-samar para penjual sayur mulai bercakap. Dan percakapan itu menyebutkan nama seseorang yang kukenal, Arni. "Kemarin katanya ia dapat setangkai bunga, dan disimpan dengan apik di kamarnya. Aku yakin jika bunga itu dari Muri, melihat betapa mimik wajahnya yang bahagia."
Kukerutkan keningku, bunga? Apakah itu bunga dariku? Atau, memang benar jika Muri telah memberinya bunga yang lain?
"Eleh, eleh... tahu dari mana kamu kalau Arni mendapatkan setangkai bunga? Perkara seperti ini kok ya kamu tahu saja. Ini, kan, perkara rumah tangga. Urusannya mereka," sekrang yang lain menimpali.
Perempuan bertubug bongsor itu tertawa, sambil mengibaskan kangkungnya yang ia pengang.
"Bagaimanapun, Arni sudah kuanggap anakku sendiri, toh, Tun. Jadi sekecil apa pun hal yang membuatnya bahagia, aku selalu ingin tahu. Aku tahu dari Ningrum, kalau di kamar biungnya ada setangkai bunga yang ia taruh di dalam gelas. Bahkan, Ningrum pun ndhak boleh menyentuh bunga itu. Katanya, itu adalah bunga dari laki-laki yang berharga, siapa lagi kalau bukan suaminya, toh?" terangnya semangat. Dan entah kenapa, aku malah tersenyum. Sebab kutahu, itu bunga pemberian dariku.
"Syukur kalau mereka sudah rukun dan Muri baik sama Arni. Kasian benar perempuan malang itu. Tapi, Pi, apa kamu ndhak dengar kabar?"
"Kabar apa, toh, Nah?" tanya wanita tua itu penasaran, jujur aku pun sama. Penasaran juga.
"Kabarnya Arni tengah bermain api di belakang Muri, Pi. Dan yang lebih bikin gonjang-ganjing lagi, laki-lakinya itu orang yang berpengaruh di kampung ini."
Napasku seolah berhenti mendengar kabar itu. Jujur, meski keduanya ndhak menyebutkan namaku. Tapi, aku merasa juga. Dan entah bagaimana itu bisa terjadi.
"Jangan ngawur, kamu! Meski miskin, Arni itu perempuan yang bermartabat, Nah. Dia itu anak dari Juragan, lho. Lancang benar kamu berkata seperti itu. Ndhak sopan!"
"Ndhak sopan bagaimana, toh, Pi. Aku ini mendengar dari warga kampung, lho. Bahkan, Muri saja sempat bercerita dengan kawan-kawannya di warung Mbah Masirah beberapa hari yang lalu."
"Jun, ayo pulang," kata Biung yang berhasil membuyarkan konsentrasiku pada percakapan dua manusia itu. Kulihat tas belanja Biung belum penuh, dan biasanya Biung betah benar kalau lama-lama di pasar.
"Tumben benar Biung sudah selesai belanja. Biasanya, siang baru pulang," kubilang. Tapi dia malah menjewerku.
"Ndhak tahu, Biung merasa hari ini ndhak nyaman saja. Orang-orang melihat Biung dengan tatapan aneh. Jadi, Biung pulang saja. Sudah kutitipkan belanjaan yang lain kepada Simbahmu. Nanti biar Sobirin atau Junet yang menjemput."
Aku diam, sambil menyalakan mesin motorku. Melaju pelan-pelan dengan pikiran yang entah ke mana. Di sisi lain aku bahagia saat tahu jika Arni memandangku sebagai orang yang berharga baginya. Tapi, aku pun ndhak mau, hanya karena hal ini sampai melukai hati Biung. Sebab bagiku, kebahagiaan dan kehormatan Biung adalah yang paling utama.
"Yen ning tawang ana lintang, ya, Dik.... Ning atiku ana Biung...." nyanyiku. Dan itu berhasil membuat Biung tertawa.
"Kamu tahu lagu itu dari mana, toh, Juna? Kok ya ada-ada saja."
"Lho, aku ini penggemar Didi Kempot garis keras, Biung. Asal Biung tahu saja. Nanti, suatu saat, aku ingin bertemu dengannya, lho."
Biung kembali tertawa, ia memeluk pinggangku sambil menyandarkan kepalanya. Aku yakin, Biung tengah bernostalgia sekarang.
"Anak muda kok sukanya lagu campur sari. Mbok ya suka dangdut atau pop begitu, lho...," serunya lagi. Tapi aku diam saja sambil cekikikan. Kalau aku nyanyi lagu dangdut atau pun pop. Pastilah Biung ndhak akan terhibur. "Jadi rindu Kang Mas Adrian," lirihnya. Jujur, sebagai anak aku merasa sakit. Entah kenapa, aku merasakan sakit yang Biung rasakan. Sakit rindu kepada Romo yang bahkan wajahnya belum sempat kupandang.
"Sama, Arjuna juga," kubilang. Ndhak ada hal apa pun yang kurasa dilakukan oleh Biung. Tapi kupikir, mungkin, dia sedang menangis sekarang karena rindu.
"Jangan bilang Romo Nathan," kata Biung.
"Kenapa?" kutanya.
"Nanti dia cemburu. Kalau dia cemburu, repot," jawabnya lagi.
Iya aku tahu, Romo Nathan adalah lelaki pencemburu nomor satu di dunia. Tapi aku juga lebih dari tahu, jika cemburunya sebanding dengan rasa cintanya kepada Biung.
"Nanti kalau Romo Nathan cemburu, cium saja, Biung. Pasti beliau senyum. Tapi kalau masih belum mempan, ajak kelon. Hahaha."
"Arjuna, lancang benar kamu berkata seperti itu kepada Biungmu ini!" marah Biung. Memang aku ini kelewatan.
"Maaf, Biung, sengaja."
"Arjuna!"
"Rindu marahnya Biung," kubilang. Tapi Biung diam saja. "Tapi lebih rindu cium sayangnya Biung," lanjutku.
"Ndhak kukasih. Kamu anak nakal," jawabnya.
"Kupaksa. Sampai Biung bilang, Juna anak baik."
"Arjuna!" marahnya lagi. Dan itu berhasil membuatku kembali tertawa.
"Arjuna sayang Biung."
"Biung lebih."