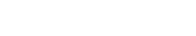IV-272. Seni Tertinggi Perang
IV-272. Seni Tertinggi Perang
.
.
"kakek ingin bicara apa?" teras sisi kanan rumah rumah induk tertangkap dua generasi berbeda duduk bersama.
tempat ini ialah pilihan tetua Wiryo, jujur mahendra sempat terkejut. bagaimana tidak, pria tua yang monoton ini biasanya meminta dirinya datang ke ruang kerja alih-alih teras yang menyajikan ruang terbuka.
"aku tidak suka dengan caramu," ketika lelaki tua itu mulai bicara entah bagaimana hujan turun seperti serabut tipis yang di sebar ke bumi.
"kapan anda pernah suka dengan cara saya?" pertanyaan yang bernada sindiran.
"Pernah kamu mendengar tentang kemenangan abadi?" pertanyaan hendra tidak di jawab wiryo. lelaki di atas kursi roda tersebut malah menyajikan pertanyaan.
seperti Wiryo, hendra pun tidak menjawab, dia hanya melirik kakeknya.
"Kemenangan bukan tentang bagaimana mengalahkan orang lain," dia yang bicara melirik membalas tatapan cucunya.
"Seni tertinggi perang, untuk menaklukkan musuh tanpa pertempuran," suaranya berat dan tentu saja pada ujung kalimatnya ada patahan tajam, khas cara bicara para lelaki Djoyodiningrat, "aku sangat yakin aku pernah memberimu pemahaman tentang ini."
Mata Wiryo menatap penuh ke arah cucunya, hendra melihatnya sekilas lalu memindahkan tatapan, "kemenangan sejati ialah kemenangan tanpa berperang. Mengapa kemenangan terbaik adalah kemenangan tanpa berperang? Karena peperangan hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,"
"mereka mengambil orangku dan berbuat semena-mena, lalu aku harus bagaimana?" hendra tidak terima kalimat kakeknya. hendra sangat tahu bagaimana kakeknya berusaha menjaga perdamaian selama ini.
termasuk menjaga sebuah situasi dimana tiap-tiap strateginya dibiarkan bias dan gelap tak terbaca sehingga musuh tak bisa menerka sebesar apa kekuatannya, tak tertembus layaknya pekatnya malam dan ketika orang-orangnya bergerak musuhnya percaya Wiryo dan segala hal yang dikendalikan bisa melampaui ledakan petir yang bisa menghanguskan apa saja.
"Jadi kamu lupa?? kamu punya otak dan mulut untuk bernegosiasi?"
Hendra tak bisa memberikan jawaban, sadar dirinya melewatkan prosedur itu.
"kekek juga lupa satu hal yang kakek ajarkan." Walaupun lelaki ini menyadari dia kurang cermat akan tetapi dia ingat satu hal yang bisa membenarkan keputusannya, "Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat. Menukik, menyerang dan menghancurkan korbannya." sempat mengambil nafas, "dan keputusanku waktu itu setara dengan apa yang baru aku ucapkan," dia ingin menyudahi perdebatan ini. sadar betul menggoyah prinsip yang ditekankan kakeknya seperti menaburi garam di atas lautan. sangat percuma.
Mungkin hendra tahu cara modern untuk meningkatkan omset bisnis, menciptakan peluang usaha baru tapi tidak dengan mengungguli kemampuan lelaki tua di atas roda ini dalam memimpin.
"aku tahu kamu jauh lebih muda dari ku, aku bahkan tahu generasi mereka yang seusiamu tak mampu menyaingi kualitasmu secara pribadi, pria tua ini hanya mengkhawatirkan tindakan ekstrim di luar kendali yang bisa saja melukai bagian dari kita,"
"mereka sudah melakukannya sejak dulu, anda terlambat menyatakan kekhawatiran ini sekarang," kalimat hendra dipenuhi penekanan, andai lawan bicaranya bukan kakeknya sangat mungkin lelaki bermata biru ini bakal menyantapnya menggunakan kalimat lain yang lebih sadis. sekuat tenaga mahendra berupaya untuk menahan diri.
"tapi mereka selalu terkendali, mereka tak bisa melampaui, berpikir berulang untuk menyentuh kita, kamu tahu kenapa?"
"cukup! ini sudah terjadi, aku tak mau menoleh kebelakang,"
"temui putra Clara, ini perintah," ujar wiryo.
"anda bukan pemimpin di sini, jangan lupa anda sudah menyerahkan jabatan anda pada saya. hak saya mengatur apa yang baik menurut saya," kilah mahendra.
"ini perintah kakek kepada cucunya,"
sejenak Hendra sempat senyap sesaat. pertama kali lelaki tua di kursi roda mengatakan kata ini adalah saat dia dipaksa menerima pernikahan dengan Aruna. dan yang kedua hari ini.
"buat apa menemui dia?" hendra masih belum mengerti apa yang diinginkan tetua wiryo.
"redam gejolak dan tanyakan motifnya mengambil dua orangmu seenaknya, pasti ada api sebelum asap membumbung tinggi," kekeh Wiryo.
"Anda ingin tahu apa apinya?"
Wiryo lekas menoleh pada Mahendra, tak menyangka ternyata cucunya bahkan sudah tahu masalahnya tapi tak mampu menyelesaikannya.
"istriku menembak putra kedua barga,"
seketika Wiryo memejamkan mata, tatkala matanya terbuka dia berujar, "bagaimana bisa itu terjadi,"
"dia mabuk berat, menghadang mobil yang membawa Aruna, istriku mempertahankan diri," nada bicara lelaki bermata biru melemah, terkesan lelah.
"itu sebabnya aku katakan berulang, jangan biarkan perempuan-perempuan kita berkeliaran," Wiryo menoleh penuh pada Mahendra, "mereka kelemahan kita," tiga kata terakhir diujarkan lirih.
"Bagaimana kamu bisa membuat oma Sukma tak tersentuh oleh mereka?"
Wiryo terbungkam sejenak, "aku menikahinya sebab Sukma muda mudah di atur," ada senyum kecil yang menggantung.
"jadi, karena oma Sukma mematuhi anda terus menerus?" duga Mahendra.
"Tidak juga,"
"lalu?" buru mahendra kepada kakeknya.
"kamu bertanya sebagai apa kepadaku saat ini?" Wiryo membuat mahendra mengerutkan alisnya. akan tetapi selepas menimang-nimang pertanyaan kakeknya lelaki bermata biru memutuskan untuk menjawab: "sebagai lelaki," lalu di ralat, "pemimpin keluarga,"
"Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu memiliki teman, atau orang dekat, yang begitu iri pada barang-barang tertentu, terutama barang yang kamu cintai?"
Mahendra terdiam, "aku tidak memiliki teman seperti itu,"
"kalau pun bukan teman, siapa saja lah. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan?"
"Siapa saja? Kehidupan ku hanya berisi karyawan dan ajudan. Mereka tak berani melakukan itu,"
"Huuuh," tetua wiryo menoleh penuh pada Mahendra. Kursinya sempat bergeser sekian inci. Selepas menatap cucunya, ujungnya dia tak bisa berkata-kata selain membuat kesimpulan sendiri: "perlakuan barang-barang itu seperti benda tak berharga, seolah-olah benda-benda itu bukan yang utama, sehingga dia tak menyentuhnya,"
"Begitu?" Ini suara Hendra. Bergeming Saat dia menyadari sesuatu, bisa jadi selama ini logika pria tua ini yang menjadikan dirinya di perlakukan layaknya bawahan yang harus menurutinya, atau robot yang di remot, alih-alih cucu yang mendapatkan kasih sayang utuh.
"Apakah itu berhasil?"
"Aku bisa mempertahankan keluarga ku sebab itu," tetua Wiryo membuka wujud asli maksud dari kiasan di kalimat sebelumnya.
Inikah alasan mengapa dia dingin bahkan pada istri, putri termasuk Hendra.
"Ah'," Hendra membuang nafas tak percaya, jika benar, hal tersebut sungguh terlalu.
"Tuan, maaf…," Hendra menoleh dan Ratna lah yang menyapanya.
"Maaf mengganggu anda,"
"Ada apa?" Ini suara Hendra.
"Nona meminta saya memanggil anda," ada anggukan kecil sebagai balasan dari Hendra.
"Jika tidak ada lagi, aku…"
"Kau terlalu memanjakannya," Wiryo memotong kalimat Hendra.
"Aku lebih suka memperlakukan barang yang aku cintai sebaik mungkin, selebihnya kusembunyikan benda itu di tempat paling rahasia, kalau perlu di lapisi tingkat keamanan tinggi. Dari pada membiarkan diriku tersiksa dengan pura-pura menjadikannya benda tak berharga,"
Mahendra berdiri meninggalkan Wiryo.
.
.
"Sayang, kamu?" Pintu ukir Jepara baru saja terbuka. Seseorang di atas sofa menoleh kepada Mahendra.
"Kamu suka rambutku?" Aruna tersenyum, menggerak-gerakkan kepalanya berulang, "aku memotongnya," tangan kanan perempuan ini naik, ujung telunjuk tangan kanan mendekati ujung ibu jari, "tenang saja hanya segini, aku tahu kamu tak suka rambutku pendek. tapi, aku rasa ini cukup cantik," Aruna mewarnai rambutnya dengan warna coklat hangat serupa dengan warna matanya, sedikit di buat berkembang, dengan poni pendek. tepat di atas alis.
"Cantik," ini suara Mahendra berjalan mendekati istrinya, 'bagaimana aku bisa mengabaikan sesuatu yang kucintai? Pemikiran tetua terlalu kolot!'